Literatur
Post-Truth Era! Benarkah Masyarakat Indonesia Anti-Intelektualisme dan Korelasinya Terhadap Kemunduran Demokrasi
Published
1 tahun agoon
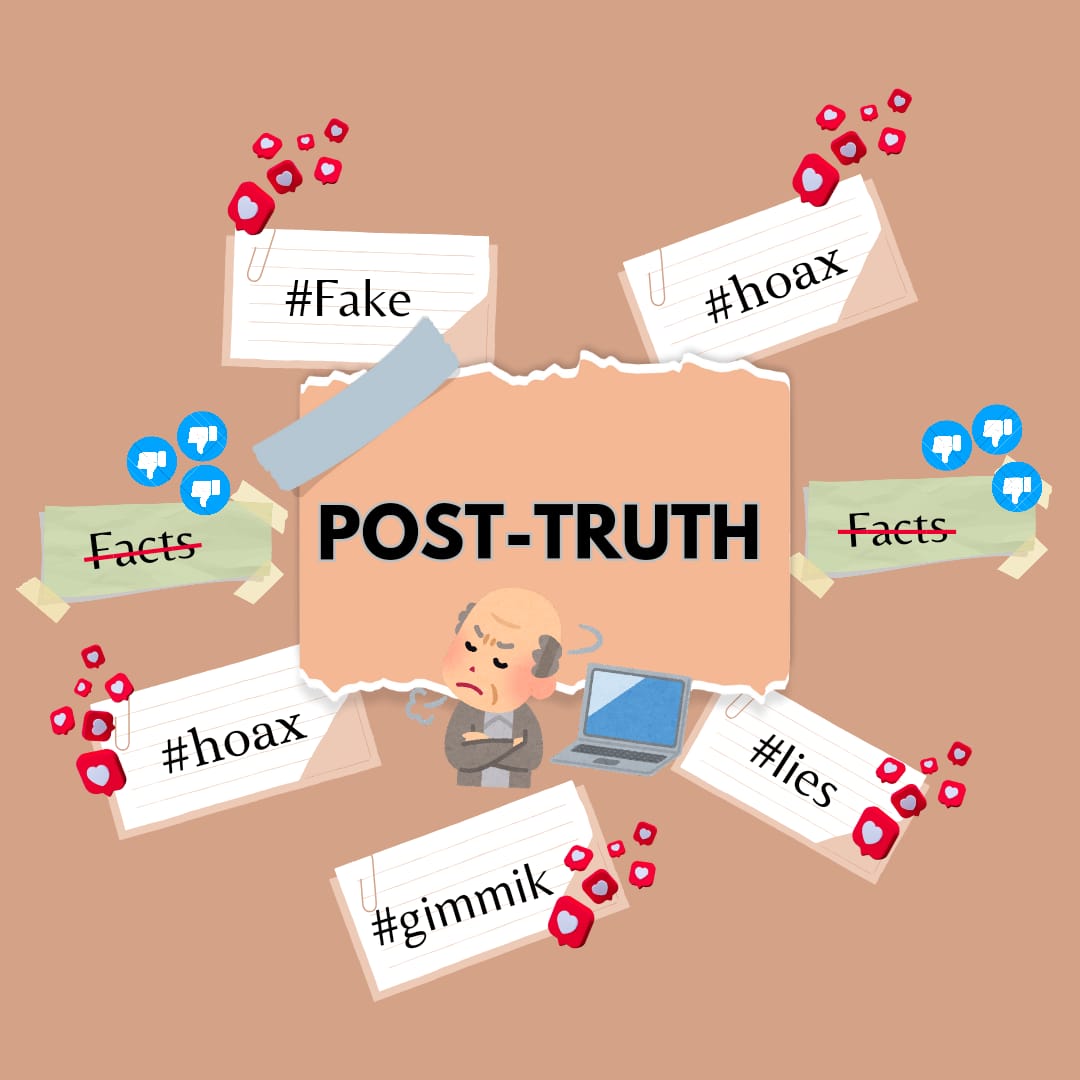
Oleh: Shinta Eka Marlina
shintaeka.m@gmail.com
Suarahimpunan.com – Masyarakat modern ditandai dengan hadirnya kecanggihan teknologi dalam setiap aspek kehidupannya. Kecanggihan teknologi mengantarkan masyarakat modern pada komunikasi berbasis online yakni media sosial. Media sosial mengambil peran penting dalam kehidupan masyarakat modern dengan menghadirkan kemudahan berkomunikasi tak terbatas jarak dan waktu, mempermudah kegiatan belajar dan bekerja, hingga yang paling krusial media sosial telah mempengaruhi cara berpikir.
Modernisasi turut menghadirkan sebuah fase yang disebut sebagai post-truth era, Menurut kamus Oxford, post-truth didefinisikan sebagai kondisi suatu keadaan dimana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding daya tarik emosional dan kepercayaan pribadi. Post-truth pada akhirnya melahirkan fenomena masyarakat anti-intelektualisme dengan hilangnya eksistensi ilmuwan atau kaum intelektual yang disebut sebagai matinya kepakaran.
Fenomena anti-intelektualisme sebenarnya bukan suatu hal yang baru, Setiap periode peradaban manusia fenomena anti-intelektualisme selalu ada dan memiliki kecenderungan yang sama. Kaum intelektual biasanya dimusuhi oleh elit penguasa karena membahayakan kepentingan dan status quo nya.
Mari kita lihat beberapa tokoh intelektual yang dimusuhi oleh elit penguasa hingga keluar masuk penjara akibat aktivitas berpikirnya. Seperti pada abad pra renaissance ketika gereja menghegemoni seluruh aspek kehidupan masyarakat, Galileo Galilei dikenal sebagai bapak sains modern, karena membuktikan Teori Copernicus semua benar soal bumi mengelilingi matahari, kalangan gereja melalui komite Inkuisisinya menarik Galileo ke pengadilan dan menjadikannya tahanan rumah seumur hidup hingga ia meninggal.
Kemudian, Paulo Freire seorang tokoh pendidikan Brasil dipenjara karena dianggap membahayakan pemerintah, Ali Shariati seorang sosiolog revolusioner Iran mengalami hal yang serupa, di Indonesia sendiri ada Tan Malaka, Buya Hamka, Pramoedya Ananta Toer dan masih banyak lagi. Dari potret ini dapat kita lihat bagaimana penguasa memusuhi kaum intelektual dari masa ke masa.
Dalam transisi politik belakangan ketika sejumlah pakar menyatakan demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan puncaknya terjadi pada pemilu 2024. Klaim ini disertai bukti-bukti konkret yang dapat disaksikan secara empirik oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Dimulai dari pembajakan MK, Ketua KPU yang sampai hari ini telah melakukan empat kali pelanggaran etik, cawe-cawe Presiden, dugaan penggunaan alat negara dan sejumlah kejanggalan lainya yang membuat kaum intelektual dari berbagai kalangan bersuara agar pemilu berjalan dengan semestinya.
Namun tindakan kaum intelektual dalam menyuarakan kritik terhadap kepemimpinan Jokowi malah mendapat respon bernada sinis oleh sejumlah orang bahkan dianggap sebagai partisan parpol dan suara kelompok yang kalah.
Apa yang menyebabkan mayoritas masyarakat Indonesia anti-intelektualisme dan bagaimana kaitannya dengan demokrasi?
Tentu ada banyak sekali teori yang dapat mengurai fenomena ini, dari filsafat tentang bagaimana manusia itu hidup berkelompok dan mempercayai satu sama lain, tentang bagaimana terciptanya kontrak sosial hingga lahirnya sebuah negara dll.
Namun dalam opini yang singkat ini, saya hanya akan mengurai fenomena tersebut dalam tiga bagian saja.
Pertama efek fanatisme, mengutip pernyataan psikolog Efnie Indrianie dalam video narasi.tv fanatisme muncul lantaran teraktivasinya amygdala (bagian pada otak manusia yang berkaitan dengan emosi) yang imbasnya seseorang tidak bisa berfikir secara logis. Seseorang yang fanatik merasa apa yang ia yakini adalah kebenaran tertinggi sehingga sulit menerima pandangan dari kelompok lain.
Dalam konteks pemilu 2024 dapat kita temukan pendukung yang fanatik dari ketiga paslon capres cawapres, mereka menjustifikasi diri sebagai pendukung garis keras. Segala sesuatu yang dianggap merugikan pasangan yang didukung meskipun fakta akan otomatis tertolak. Padahal ketiga paslon pasti punya kekurangan masing-masing yang seharusnya bisa jadi celah untuk masyarakat pelajari lebih lanjut sehingga pertimbangan dalam menentukan pilihan dapat dilakukan secara rasional.
Kedua pengaruh media sosial, seperti yang telah disinggung di bagian awal tadi bahwa media sosial telah menghegemoni cara berfikir masyarakat. Mengutip dalam sumber yang sama narasi.tv, Ball rokeach, Melvin Lawrence defleur menjelaskan teori efek ketergantungan media, teori ini berpendapat masyarakat bergantung pada media sebagai sumber informasi dan pengetahuan.
Apabila seseorang terpapar dengan satu informasi secara terus menerus, maka informasi itu yang akan mereka percayai. Fenomena buzzer dan influencer misalnya, ketika seseorang memfollow influencer yang menyajikan informasi tertentu, algoritma media sosial akan mengendalikan timeline seseorang tersebut sehingga menutup kemungkinan adanya informasi-informasi tandingan yang menyebabkan seseorang hanya mengkonsumsi informasi serupa walaupun dalam konten yang berbeda. Maka informasi yang diperoleh secara terus-menerus tadi akan menjadi kebenaran meskipun belum pasti kredibilitasnya apalagi informasi dari akun-akun anonim”buzzer”.
Bahwa betul seseorang boleh saja mempercayai influencer selama informasi yang mereka berikan sesuai dengan data dan fakta yang objektif. Walaupun demikian seorang yang kritis akan mencari dan mempelajari lebih lanjut tentang informasi apa yang ia terima. Sayangnya, di tengah sulitnya kehidupan, bagi sebagian orang terkadang berpikir kritis itu sulit dan ribet sehingga informasi yang diterima sesuai dengan keinginan emosional dan kepercayaan pribadi saja.
Ketiga, Matinya kepakaran tidak terlepas dari peran pemerintah yang mengensampingkan peran kepakaran itu sendiri. Perlu saya ingatkan kembali bahwa dalam prosedur pembuatan produk kebijakan negara ada yang namanya naskah akademik yang disusun melalui riset oleh sejumlah ilmuan atau akademisi. Hasil dari penelitian para pakar inilah yang kelak akan menjadi instrument penting untuk menjadi tolak ukur kesesuaian atau tidaknya suatu kebijakan.
Rizki Argama direktur eksekutif PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) dalam diskusi STH-Jentera mengatakan situasi beberapa tahun belakangan melahirkan kebijakan Anti Sains. Seperti Permendagri No.3/2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian yang berpotensi memperlambat proses riset dan inovasi. Secara tupoksi yang relevan aktivitas penelitian bidang riset dan inovasi seharusnya bukan kewenangan Kemendagri tetapi kewenangan Kemdikbud Ristek. Sehingga pengaturan izin penelitian di bawah Kemendagri menimbulkan kerancuan bahkan terjadi tumpang tindih kewenangan yang berpotensi memberikan hambatan birokrasi bagi aktivitas penelitian.
Kemudian UU No.11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Secara umum UU ini memberikan kemudahan dan fasilitas kepada peneliti atau akademisi terkait inovasi penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Namun masih memuat pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi peneliti karena aktivitas penelitiannya.
Ada pasal-pasal membatasi peneliti asing yang melakukan penelitian di Indonesia, apabila peneliti asing tidak memperoleh izin administrative maka dapat dipidana, padahal kalau dilihat kesesuain antara proses yang dilakukan dengan sanksinya maka seharusnya sanksi yang didapat adalah sanksi administratif bukan pidana.
Kemudian ada pasal-pasal ancaman pidana terhadap aktivitas penelitian yang dianggap “membahayakan”. Pada implementasinya di lapangan penegak hukum atau penguasa akan memiliki justifikasi terhadap apa yang mereka tafsirkan sebagai “penelitian yang membahayakan” dan dalam praktiknya akan membahayakan para peneliti.
Lebih lanjut Argama menjelaskan sebuah teori dari seorang ahli kebijakan publik asal Inggris, Philip Davis, bahwa pembentukan kebijakan dengan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policymaking) diharapkan menjadi penyeimbang terhadap kebijakan berbasis opini (opinion-based evidence policymaking) dan jantung dari proses pembentukan kebijakan berbasis bukti adalah hasil penelitian.
Dalam praktiknya di beberapa tahun terakhir, dapat kita temui produk kebijakan pemerintah yang dibuat tanpa melibatkan naskah akademik yang memadai. Bahkan beberapa UU dibuat dalam tempo sesingkat-singkatnya dan mengabaikan suara dan penolakan dari masyarakat sipil.
Anti-intelektualisme juga terlihat dalam kasus Haris-Fatia, ketika menyuarakan soal temuan penelitian atau hasil riset dari sejumlah organisasi, seperti KontraS, Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD dibalik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua kepada khalayak melalui media podcast youtube.
Lalu penguasa menjustifikasi Haris-Fatia melalui UU ITE untuk membungkam kritiknya. Lagi-lagi dalam sejarah yang sedikit dibahas di awal, penguasa selalu saja memusuhi kelompok intelektual yang dianggap membahayakan dan mengganggu status quo nya. Penguasa akan melakukan segala cara untuk menjustifikasi kaum intelektual melalui manipulasi, propaganda bahkan penggunaan instrumen negara baik hukum maupun aparat.
Masyarakat yang akses intelektualnya kurang memadai akan dengan mudah percaya terhadap propaganda penguasa sehingga ikut anti terhadap intelektualisme. Ketiga pemaparan diatas setidaknya menjadi penyebab mengapa masyarakat Indonesia anti-intelektualisme.
Ketika bukti-bukti ilmiah tidak lagi menjadi landasan dalam menentukan kebenaran, inilah yang disebut post-truth era atau masyarakat anti-intelektualisme. Jika produk kebijakan tidak melibatkan riset dan naskah akademik yang memadai maka negara bekerja berdasarkan basis keinginan semata bukan basis ilmiah, konsekuensinya akan mengacaukan sistem demokrasi yang dimana hal fundamentalnya adalah partisipasi masyarakat dalam hal ini yakni sumbangsih pikiran.
Kebenaran memang tidak bersifat final, namun sebagai manusia yang berakal dan berfikir kita perlu meninjau standar kebenaran dengan sudut pandang yang objektif dan rasional. Kebenaran juga tidak dimonopoli oleh kaum intelektual saja, kebenaran mempunyai tolak ukur tersendiri. Namun jika kebenaran yang disampaikan oleh kelompok intelektual tersebut didukung dengan dalil-dalil yang kuat, pembuktian empiris dan rasional tentu kebenaran itu perlu untuk di pertimbangkan. (RP/Red)
Bibliography
Argama, R. (2024). Mau kemana Indonesia setela enam kali pemilu pasca-reformasi. Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Jentera.
Narasi.tv. (2024). ko bisa orang fanatik sama capres? Narasi.tv.
Rizal, J. G. (2022, 09 01). Melihat Kembali Sejarah Kemunculan Istilah Post-truth. Retrieved from Kompas.com: https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/09/060600682/melihat-kembali-sejarah-kemunculan-istilah-post-truth-?page=all
You may like
-


Matinya Demokrasi Indonesia
-


Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pemilihan Umum: Tantangan dan Prospek di Era Digital
-


Edukasi Pemilih Pemula Jelang Pemilu 2024, HMI MPO Cabang Serang Gelar Simposium Kepemudaan Gandeng KPU, Bawaslu Provinsi Banten dan Akademisi.
-


Dinamika Kontestasi Politik di Indonesia Menjelang Pesta Demokrasi 2024

Duh, Pengurus Besar HMI MPO Diduga Minta-minta THR Pakai Surat Resmi

Polda Banten Bersama Gerakan Mahasiswa Pamarayan Sinergi Ciptakan PSU Kabupaten Serang Kondusif






